Oleh: NANI EFENDI
Mengapa di Indonesia para pemudanya berebutan untuk jadi PNS? Mengapa setiap ada penerimaan PNS peserta tesnya selalu membludak seperti orang demo mau menurunkan presiden dari jabatannya? Bahkan, mereka rela berdesak-desakan, terinjak-injak, dan pergi ke daerah yang jauh-jauh hanya untuk mendapatkan nomor peserta tes dan ikut tes CPNS. Kalau ditanya, khususnya anak-anak muda, jawabannya relatif sama: jadi PNS itu enak, nyaman, aman masa depan, bisa memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, mendapat gaji yang lumayan besar yang setiap tahun naik, dan lain-lain jawaban yang serupa. Jarang sekali saya mendengar jawaban, “Ingin mengabdi pada negara dan melayani masyarakat”.
Semangat mereka kebanyakannya sama: ingin enak dan tak ingin susah, ingin dihormati, ingin dilayani dan bukan melayani, ingin menguasai, ingin mengatur, dan ingin memerintah. Persis seperti mental kebanyakan para ambtenaar zaman penjajahan Belanda di masa lalu. Dulu, zaman pemerintahan Hindia Belanda, PNS atau pegawai negeri dinamakan “ambtenaar”. Dalam struktur sosial masyarakat zaman kolonial Belanda di masa lalu, para ambtenaar digolongkan sebagai kaum priyayi, yaitu kaum yang tergolong ke dalam kelas atas masyarakat yang masih feodal.
Pramoedya Ananta Toer, seorang penulis besar Indonesia yang pernah jadi kandidat pemenang Nobel, dalam bukunya Sang Pemula, menjelaskan karakter dan mental kaum ini, yaitu: konsumtif, tidak produktif, dan tidak kreatif. Watak dan impian kasta ini adalah hal-hal yang bersifat simbol seperti pangkat dan kehormatan, bintang, payung, selempang, pita, dan gelar. Gelar tertinggi yang mereka impikan adalah: Pangeran, Arya, Adipati, dan Tumenggung. Sedangkan pangkat yang mereka gairahi adalah bupati—pangkat tertinggi di luar daerah kerajaan yang dapat dicapai oleh Pribumi pada zaman penjajahan Belanda (lihat Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula, 1985: 14).
Tidak ada kebebasan berpikir dalam kasta ini. Mereka terkekang oleh budaya yang penuh dengan kehormatan yang irasional dan semu. Oleh karenanya, pemuda dan pemudi yang berasal dari keluarga ningrat atau priyayi atau keluarga kelas bangsawan, namun mereka terpelajar dan berpikiran maju, mereka pada umumnya memilih keluar dari “kekangan” sistem keluarganya. Beberapa contoh, misalnya, HOS Tjokroaminoto, R.A. Kartini (tokoh emansipasi wanita Indonesia), Bung Karno, Tjipto Mangoenkoesoemo, Dewi Sartika, Tirto Adhi Soerjo (Bapak Pers Indonesia), dan lain-lain.
Tidak ada kebebasan berpikir dalam kasta ini. Mereka terkekang oleh budaya yang penuh dengan kehormatan yang irasional dan semu. Oleh karenanya, pemuda dan pemudi yang berasal dari keluarga ningrat atau priyayi atau keluarga kelas bangsawan, namun mereka terpelajar dan berpikiran maju, mereka pada umumnya memilih keluar dari “kekangan” sistem keluarganya. Beberapa contoh, misalnya, HOS Tjokroaminoto, R.A. Kartini (tokoh emansipasi wanita Indonesia), Bung Karno, Tjipto Mangoenkoesoemo, Dewi Sartika, Tirto Adhi Soerjo (Bapak Pers Indonesia), dan lain-lain.
Bahkan, Tirto Adhi Soerjo mengatakan, menjadi pegawai negeri kolonial menghilangkan kemerdekaan diri dan kebebasab berpikir. Mereka ini adalah beberapa contoh dari anggota keluarga ningrat atau priyayi yang tidak memiliki mental priyayi. Mereka-mereka ini tidak tertarik untuk menjadi ambtenaar atau pegawai negeri. Mereka memilih bebas. Mereka tidak bersikap seperti kaum priyayi. Kebanyakan mereka bersahaja, bebas berpikir, bebas berkumpul, dan bebas berserikat, karena dengan begitu mereka bisa berbuat sesuatu yang benar-benar nyata untuk kepentingan rakyat.
Bung Karno, Bung Hatta, dan aktivis-aktivis pejuang bangsa zaman dahulu pernah ditawari untuk bekerja sebagai ambtenaar (pegawai negeri), tapi mereka tolak mentah-mentah. Mereka sedikit pun tidak tertarik jadi ambtenaar. Mereka lebih memilih menjadi aktivis pergerakan. Jadi ambtenaar (PNS pada saat itu), dalam pandangan mereka, bukanlah jalan atau alat perjuangan. Menjadi pegawai negeri ketika itu sama saja dengan mengabdi pada kepentingan kolonial. Kalau mereka jadi PNS saat itu, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah memerdekakan bangsa ini. Sebagian besar waktu mereka tentu akan tersita oleh kesibukan sebagai pekerja kantor dengan segala rutinitas, formalitas dan tetek bengeknya, sehingga mereka tidak sempat lagi untuk membaca buku dan berorganisasi atau mendirikan organisasi-organisasi pergerakan.
Bung Karno, Bung Hatta, dan aktivis-aktivis pejuang bangsa zaman dahulu pernah ditawari untuk bekerja sebagai ambtenaar (pegawai negeri), tapi mereka tolak mentah-mentah. Mereka sedikit pun tidak tertarik jadi ambtenaar. Mereka lebih memilih menjadi aktivis pergerakan. Jadi ambtenaar (PNS pada saat itu), dalam pandangan mereka, bukanlah jalan atau alat perjuangan. Menjadi pegawai negeri ketika itu sama saja dengan mengabdi pada kepentingan kolonial. Kalau mereka jadi PNS saat itu, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah memerdekakan bangsa ini. Sebagian besar waktu mereka tentu akan tersita oleh kesibukan sebagai pekerja kantor dengan segala rutinitas, formalitas dan tetek bengeknya, sehingga mereka tidak sempat lagi untuk membaca buku dan berorganisasi atau mendirikan organisasi-organisasi pergerakan.
Dan kemungkinan juga mereka tidak akan pernah jadi orang besar sebagaimana yang kita kenal. Mengapa? Ya, karena kebebasan berpikir dan ruang gerak mereka menjadi sempit dan terbatas. Mereka terikat dalam sistem yang bersifat formalistik-simbolik. Oleh karenanya, Tjipto Mangoenkoesoemo mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai ambtenaar (pegawai negeri) karena ia ingin bebas bergerak, berpikir, dan bersuara.
Namun anehnya, kebanyakan pemuda di Indonesia saat ini tidak menjadikan mereka-mereka itu sebagai salah satu sumber inspirasi. Kebanyakan pemuda kini tetap punya kemauan yang besar untuk jadi pegawai negeri, walaupun dengan jalan menyogok ratusan juta rupiah. Suatu budaya yang salah. Sumber budaya yang salah itu, kalau kita lihat dari latar belakang historisnya, ya dari sistem budaya feodal di Indonesia pada masa lalu itu. Budaya feodal itulah yang masih diwarisi oleh masyarakat modern Indonesia dewasa ini.
Di masa kolonial, kasta bangsawan-priyayi dipandang sebagai kasta tertinggi dan terhormat. Walaupun pada hakekatnya adalah kehormatan semu dan irasional. Nah, mental priyayi di masa lalu itu pada kenyataannya masih diwarisi juga oleh sebagian besar PNS saat ini. Kebanyakan orang masih menganggap pekerjaan sebagai PNS adalah pekerjaan yang prestisius dan dianggap seperti “kasta bangsawan-priyayi” di masa lalu. Padahal, kalau kita mau menilainya secara rasional, anggapan seperti itu tidaklah berdasar. Irasional. Semestinya, manusia itu dihormati bukanlah dari status sosialnya, tetapi dari kontribusinya bagi peradaban dan kehidupan manusia.
Oleh karena itu, dalam rangka refomasi birokrasi saat ini, PNS sudah seharusnya meninggalkan mental priyayi, yang—dalam pandangan Pramoedya—sebagaian besarnya gila hormat dan gila jabatan. Mental PNS yang harus dibangun kedepan adalah mental melayani, bukan mental dilayani. PNS harus menjauhkan perilaku eksklusif. PNS yang baik adalah PNS yang menyadari bahwa ia digaji dari uang rakyat. Oleh karena itu, ia harus melayani rakyat secara tulus ikhlas.
Namun anehnya, kebanyakan pemuda di Indonesia saat ini tidak menjadikan mereka-mereka itu sebagai salah satu sumber inspirasi. Kebanyakan pemuda kini tetap punya kemauan yang besar untuk jadi pegawai negeri, walaupun dengan jalan menyogok ratusan juta rupiah. Suatu budaya yang salah. Sumber budaya yang salah itu, kalau kita lihat dari latar belakang historisnya, ya dari sistem budaya feodal di Indonesia pada masa lalu itu. Budaya feodal itulah yang masih diwarisi oleh masyarakat modern Indonesia dewasa ini.
Di masa kolonial, kasta bangsawan-priyayi dipandang sebagai kasta tertinggi dan terhormat. Walaupun pada hakekatnya adalah kehormatan semu dan irasional. Nah, mental priyayi di masa lalu itu pada kenyataannya masih diwarisi juga oleh sebagian besar PNS saat ini. Kebanyakan orang masih menganggap pekerjaan sebagai PNS adalah pekerjaan yang prestisius dan dianggap seperti “kasta bangsawan-priyayi” di masa lalu. Padahal, kalau kita mau menilainya secara rasional, anggapan seperti itu tidaklah berdasar. Irasional. Semestinya, manusia itu dihormati bukanlah dari status sosialnya, tetapi dari kontribusinya bagi peradaban dan kehidupan manusia.
Oleh karena itu, dalam rangka refomasi birokrasi saat ini, PNS sudah seharusnya meninggalkan mental priyayi, yang—dalam pandangan Pramoedya—sebagaian besarnya gila hormat dan gila jabatan. Mental PNS yang harus dibangun kedepan adalah mental melayani, bukan mental dilayani. PNS harus menjauhkan perilaku eksklusif. PNS yang baik adalah PNS yang menyadari bahwa ia digaji dari uang rakyat. Oleh karena itu, ia harus melayani rakyat secara tulus ikhlas.
Menjadi PNS bukan berarti “menjadi ningrat” atau menjadi “kasta bangsawan-priyayi”. PNS hanyalah abdi negara. Mereka punya kewajiban mengabdi pada kepentingan rakyat—karena ia memang hidup dari uang rakyat. Terlalu mahal rakyat menggaji kalau orientasi mereka hanya ingin enak, foya-foya, dan tidak produktif. Dan terlalu mahal mereka digaji dengan uang rakyat kalau hanya ingin dilayani namun enggan melayani masyarakat. Beban anggaran negara kita sudah terlalu berat menanggung biaya pegawai.
NANI EFENDI
Alumnus LK III HMI
NANI EFENDI
Alumnus LK III HMI

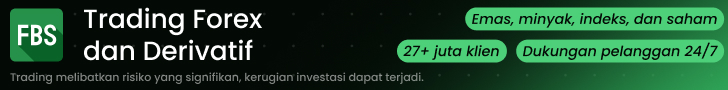





.jpg)

0 Komentar